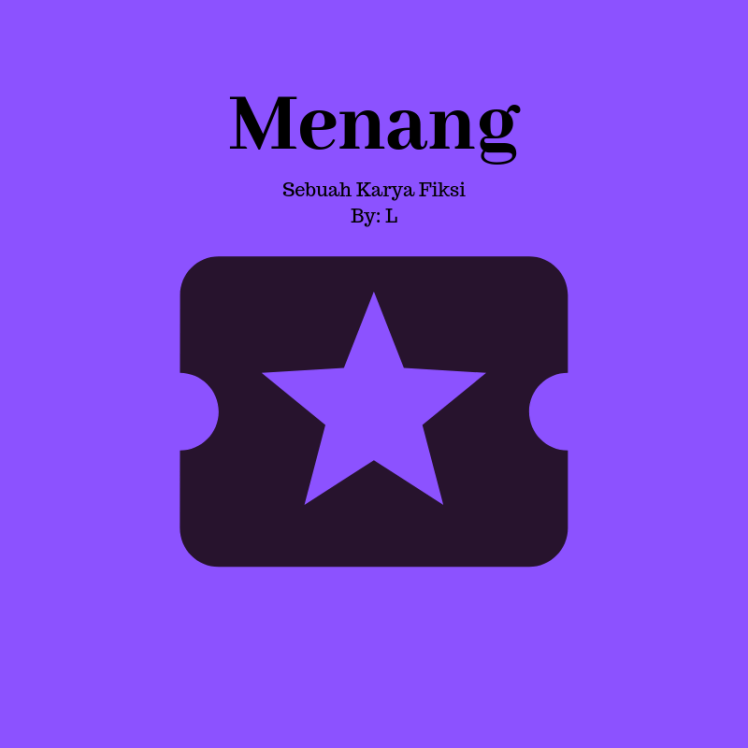
“Aku harus menyampaikan sesuatu. Pokoknya harus.”
Dua jam yang lalu, aku akhirnya memutuskan untuk menggenggam handphone dan mulai menuliskan sesuatu. Harus. Tapi, buntu. Alhasil begini saja terus, tak jelas mau apa.
“Ni, udah jam 9 malam loh. Masih betah aja?”
Leo. Seorang sweetheart lantai 23 yang sayangnya tidak bisa menjadi sweetheart siapapun lagi. Sudah bercincin, cyn. “Oh, iya. Sebentar lagi.”
“Jangan kerja melulu, Ni. Nikmati hidup sedikit.”
Aku mengangkat sudut bibirku tipis, “Iya. Sudah pulang sana. Pasti sudah ditunggu di bawah. Jangan sampai doi naik lagi ke lantai atas, sambil melontarkan kata-kata cheesy. Geli dengernya dari mulut suamimu yang berotot itu.”
Ruangan yang tadinya sepi segera terisi oleh tawa kecil.
“Oke deh. Duluan ya”
Akhirnya… Tanpa gangguan lagi.
Lekas perhatianku kembali ke handphone di genggaman tangan, yang kursornya sejak tadi terus berkedip, seakan berteriak memaksaku untuk memulai proyek penuntasan segalanya.
Tapi, bagaimana cara menyelesaikan sesuatu yang tidak pernah dimulai?
Aku menarik nafas panjang lagi. Pikiran-pikiran aneh mulai memenuhi kepalaku; Bagaimana kalau dia salah paham? Bagaimana kalau ini tidak seperti yang aku pikirkan?
Bagaimana kalau masih ada kesempatan? Bagaimana kalau aku hanya perlu bersabar sedikit lagi? Bagaimana kalau? Bagaimana kalau?
Ah… Sialan memang menjadi seorang pemikir.
Namun, suara Mia saat makan siang tadi memenuhi kepalaku, “Tidakkah kau pikir bahwa telah tiba saatnya untuk menutup sesuatu yang sudah terlalu lama abu-abu?”
Aku menarik nafas panjang. Seperti yang sudah-sudah, rasa sakit yang amat familiar lekas memenuhi kepala, tulang-tulang, jantung, bahkan paru-paruku. Persetan memang siapapun yang berkata bahwa perkara ini sangat mudah.
Tes… Tes…
Tuh kan. Kalau bicara masalah ini aku pasti menangis. Aku tidak membenci air mata, hanya tidak menyukainya, dan tidak pernah ingin bersahabat dengannya.
Kulirik ponselku yang masih bergeming dalam kepalan. Apa aku telpon Mia dulu? Ah tapi nanti aku malah disemprot. Biar bagaimanapun, tadi siang Mia sudah bicara panjang lebar, bahkan mendikte semua hal yang harus aku lakukan.
Aduh, sudah semakin malam. Ya sudah lah, kuberanikan diri untuk merangkai kata-kata yang (menurutku) seharusnya terkatakan.
Hai, ini aku, Nia. Aku sengaja memperkenalkan diriku sekali lagi karena kemarin malam kau sudah memperlakukan aku seakan kau tidak pernah mengenalku, bahkan seakan lebih tidak penting daripada seorang di pinggir jalan. Memang enak sih ya pergi dan berlari dari janji atau sesuatu yang kepalang terucap padahal sesungguhnya tak mau dilakukan.
Kau tahu, aku menunggumu, sekitar dua jam, karena kau bilang ingin bicara denganku, tentang sesuatu yang bahkan aku tidak tahu apa. Aku betul – betul menunggumu, dengan itikad baik.
Kupikir, kau akan meluruskan, merespons, atau menanggapi pengakuanku untukmu bertahun-tahun yang lalu.
Baru sekarang aku mengerti siklus yang sesungguhnya selama ini kubiarkan menjebak diriku sendiri; aku akan mengejarmu, kau melirik sedikit, kau pergi, aku mengejarmu, kau sedikit bicara, aku senang, kemudian kau pergi lagi, begitu terus, selama bertahun – tahun. Tolol ya bahwa itu baru kumengerti sekarang.
Kesalahan pertama yang kulakukan; di momen pertama kali aku menyadari aku harus menurunkan standar-ku demi bisa bersamamu, seharusnya aku meninggalkanmu saja. Bodohnya, aku tidak melakukan itu, berharap kau atau keadaan akan berubah.
Kedua, aku meletakkan harapanku, entah untuk dicintai, diterima, atau diperlengkapi, di pundakmu. Seharusnya aku tidak pernah menggantungkan harapanku yang itu di pundak siapapun, apalagi kau.
Terakhir, kau melukaiku. Sangat. Aku tau kau tidak peduli. Maka aku juga tidak akan peduli lagi. Namun aku harus berkata ini sekarang karena aku peduli akan nasib masa depanmu; kau tidak bisa sembarangan melakukan hal semacam kemarin malam ke semua orang. Mungkin aku bisa. Tapi aku sangat yakin bahwa di luar sana, tidak ada seorang manusia pun yang mau diperlakukan sama sepertiku. Pelajari itu baik-baik ya.
Maafkan aku karena telah meletakkan harapan di pundakmu. Dan terima kasih karena sudah melukaiku.
Dengan Hormat,
Nia
Seakan baru kembali dari dimensi lain, aku menarik kembali kesadaranku. Astaga, ternyata aku bisa menulis seberani dan sepanjang ini, ya. Hebat juga. Kubaca kata-kata itu berkali-kali.
Aduh, kirim tidak ya. Kirim. Tidak. Kirim. Tidak.
S
Wajah Mia tiba-tiba seakan berlalu di hadapanku dan berkata, “Apa kau yakin kau layak diperlakukan seperti itu?”
Aku menarik sudut bibirku seperti seorang tokoh antagonis dalam novelku. Ya, Mia benar. Aku tidak layak diperlakukan seperti ini.
Akhirnya, kutekan tombol itu, Send. Selepasnya, meski cukup was-was atas respon yang akan kuterima, aku membereskan barang-barangku untuk segera pulang. Tidur sepertinya akan membantu.
Esok paginya, aku cukup terkejut karena kali ini, hanya butuh sekitar dua jam untuk menerima balasannya. Tampaknya, ia membalas kala aku sudah tertidur semalam.
Tadinya kupikir aku akan menangis histeris melihat responnya. Kenyataannya, tanpa bisa kukendalikan, aku malah tertawa terbahak-bahak demi membaca respons yang tentu saja amat kurang ajar, dengan bunyi kurang lebih seperti ini;
“Aku tidak bermaksud seperti itu. Dan ya, kau tidak boleh membiarkan seseorang memperlakukanmu seperti itu. Kuharap kau segera menyudahi perasaanmu padaku”
Mia benar. Memang ciri – ciri pria brengsek, bahkan tidak ada permintaan maaf terucap. Aku tidak lagi peduli ataupun mau untuk membaca keseluruhan bualan basi darinya.
Memang puas rasanya ketika kembali duduk di kursi kemudi, mengendalikan perasaanku sendiri. Lekas kubuka fitur delete conversation.
Ketika seluruh pesan yang pernah ada di antara kami hilang, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun aku merasa menang. Aku memang tidak sembari melihat kaca, tapi aku yakin sekali mukaku sangat menyebalkan, seperti ketika sedang memerankan salah satu karakter antagonis dalam film atau panggung pementasan-ku. Biarlah, tak peduli juga.
Puas. Puas. Puas! Aku bahkan lupa bahwa aku sempat menangis beberapa saat sebelum mengirim pesan itu. Ternyata kan terbukti bahwa orang yang ditangisi pun memang sama sekali tidak layak.
Oh, jadi ini toh rasanya menang.
Jakarta,
02.21.2019
